Prolog
Di zaman ketika teknologi mampu menulis puisi, menyusun esai, bahkan membuat skenario film dalam hitungan detik, muncul satu pertanyaan penting: masih perlukah kita belajar menulis? Bukankah kecerdasan buatan seperti AI sudah bisa “menuliskan” segalanya untuk kita?
Benar, GPT, ChatGPT, dan berbagai alat sejenis dapat menghasilkan teks dengan cepat. Namun, kecepatan tak selalu berbanding lurus dengan kualitas. Tulisan yang baik bukan sekadar tersusun rapi secara teknis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat—dan karakter itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini oleh penulisnya. Sebuah tulisan pada dasarnya adalah cerminan dari isi pikiran dan isi hati, yang sangat dipengaruhi oleh pandangan hidup si penulis.
Saat ini, banyak orang mulai memanfaatkan AI untuk berbagai kebutuhan menulis, dari email, iklan, pesan promosi, undangan, hingga karya akademik seperti artikel ilmiah, skripsi, tesis, bahkan disertasi.
Dari sisi teknis, hal ini tampak efisien. Namun dari sudut pandang akademik, filosofis, bahkan psikososial, ketergantungan penuh pada AI dalam proses menulis bisa menimbulkan masalah. Terutama jika kita bicara tentang proses belajar dan bertumbuh secara intelektual—dan lebih luas lagi, dalam konteks budaya literasi.
Lalu, Apa yang Terjadi Jika Kita Sepenuhnya Mengandalkan AI?
Banyak konsekuensinya. Salah satunya: tulisan menjadi generik dan kurang orisinal. Meskipun AI terus dikembangkan agar bisa terdengar “lebih manusiawi”, pada dasarnya bahasa yang digunakan tetap saja bahasa mesin. Tulisan dari AI sering kali terasa kering, kurang rasa, dan minim kedalaman psikososial maupun spiritual. Kata-katanya bisa saja indah dan teratur, tetapi tetap terasa hambar dan tanpa ruh.
Dalam dunia kepenulisan, kita mengenal ungkapan, “Apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati; yang hanya keluar dari mulut, masuknya pun hanya ke telinga.” Jika tulisan manusia pun harus lahir dari hati agar memiliki makna, bagaimana dengan tulisan yang sepenuhnya dihasilkan oleh mesin, yang tak memiliki perasaan?
Dampak lainnya adalah hilangnya pengembangan gaya menulis pribadi. Padahal, setiap penulis sejatinya punya gaya khas yang mencerminkan cara berpikir dan logika mereka. Saya, misalnya, bisa mengenali tulisan-tulisan dari Adian Husaini, Ilham Jaya, Tere Liye, Salim A. Fillah, atau Anwar Jaelani tanpa perlu melihat nama penulisnya—cukup dari alur dan pilihan katanya.
Ketergantungan pada AI juga dapat membuat kreativitas tumpul. Penulis tidak terbiasa berpikir kritis dan analitis, tidak terlatih menggali akar persoalan secara mendalam dengan melibatkan nalar dan rasa secara bersamaan. Akibatnya, kemampuan untuk menemukan solusi secara otentik—dengan melibatkan dimensi intelektual dan spiritual sekaligus—ikut tergerus.
Mengapa Belajar Menulis Masih Relevan?
Menulis bukan sekadar merangkai kata menjadi kalimat, tetapi proses menyusun gagasan ke dalam bentuk teks yang bermakna. Gagasan itu bisa berupa afirmasi terhadap nilai-nilai positif, atau penolakan terhadap hal-hal yang keliru dan merusak. Namun, keduanya hanya mungkin dilakukan oleh penulis yang memiliki kemampuan berpikir analitis dan kritis.
Berpikir kritis di sini bukan berarti gemar menyalahkan atau sekadar melontarkan opini tanpa dasar. Sebaliknya, ia adalah kemampuan menyaring informasi, melihat persoalan dari berbagai sudut pandang, dan melahirkan ide yang tajam—berlandaskan pengetahuan, dibalut dengan kejernihan spiritual, ketulusan hati, serta integritas pribadi.
Menulis juga merupakan bentuk ekspresi diri yang unik dan personal. Gaya, diksi, dan sudut pandang yang dipilih mencerminkan kepribadian dan cara berpikir penulisnya. Dalam tulisan yang autentik, pembaca dapat merasakan suara batin penulis, bahkan ketika mereka belum pernah saling mengenal.
Kualitas sebuah tulisan sangat ditentukan oleh kedalaman ide, keluasan wawasan, arah hidup, serta nilai-nilai yang dipegang oleh penulisnya. Karena itulah, setiap tulisan sejati punya keunikan tersendiri—ia merupakan ekspresi diri yang personal, yang lahir dari isi hati dan isi kepala penulis.
Tulisan mencerminkan pesona dan kepribadian seseorang, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara psikososial, moral, dan spiritual. Saya meyakini bahwa hanya tulisan yang orisinal—yang lahir dari kejujuran pikiran dan ketulusan jiwa—yang benar-benar bisa menyentuh pembaca secara emosional, psikologis, dan spiritual.
Oleh karena itu, belajar menulis dan terus menulis tetap relevan, bahkan sangat penting, di tengah kemajuan teknologi kecerdasan buatan dengan segala kelengkapan tools-nya. AI memang bisa menjadi alat bantu, co-writer, atau asisten penyelaras akhir. Perannya lebih kepada merapikan aspek teknis: memperbaiki kesalahan ketik, menyempurnakan tata bahasa, atau melengkapi data statistik (jika diperlukan). Contohnya tulisan ini. Dirapikan oleh AI melalui ChatGPT.
Namun, gagasan besar dan narasi yang orisinal tetap hanya bisa lahir dari penulis sejati—manusia yang berpikir, merasa, dan hidup dengan kesadaran penuh. Di situlah letak kekuatan tulisan: bukan pada kecanggihan alat, tapi pada keutuhan jiwa yang menuliskannya.
#SalamLiterasi


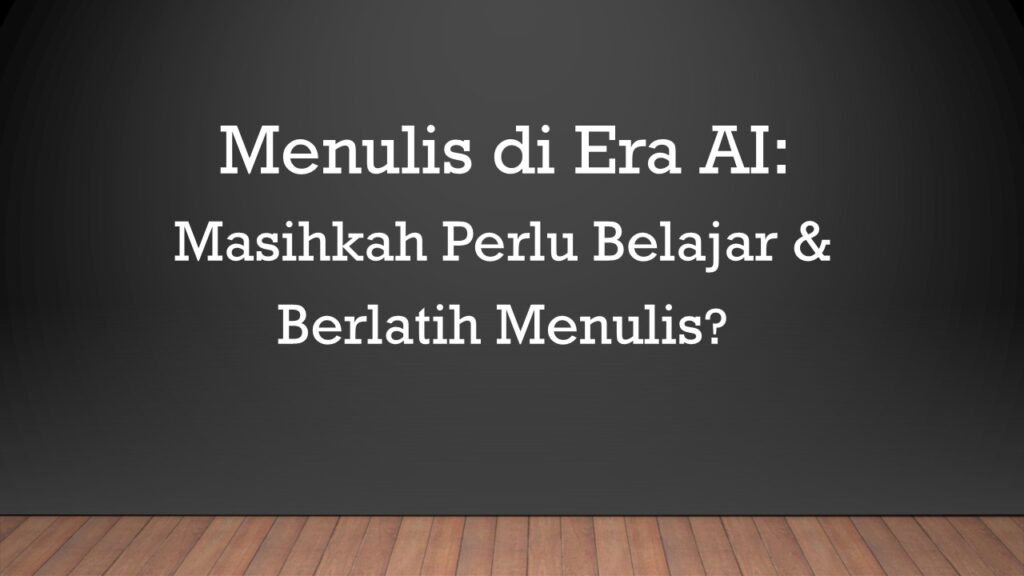

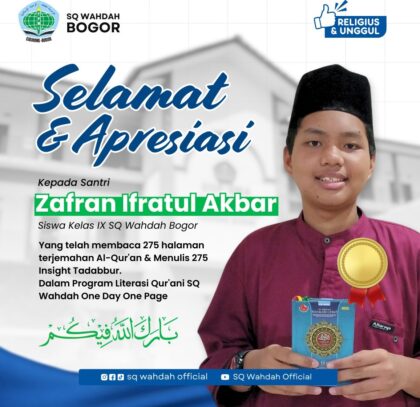
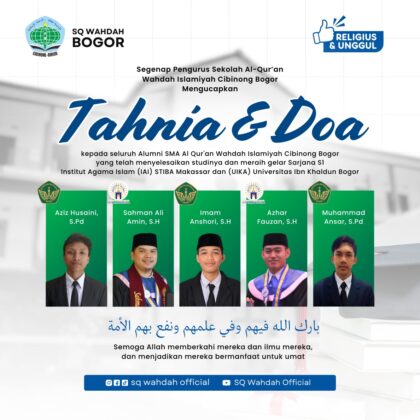
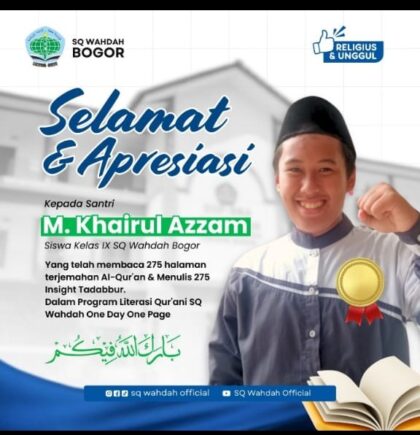


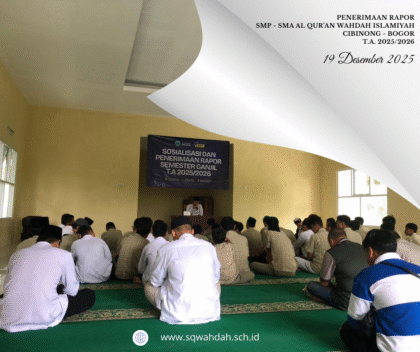

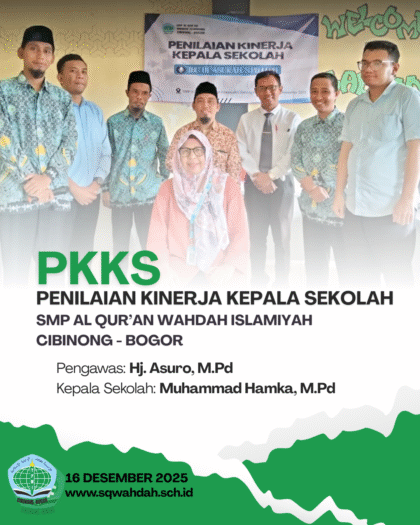




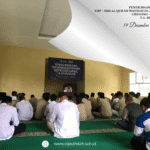
Komentar