Lampu Minyak dan Mimpi yang Menyala(Kisah Udin, Santri dari Pesisir Pulau Muna)
Setiap kali suara azan maghrib berkumandang dan cahaya jingga menggantung di ujung langit, hatinya seolah ditarik kembali ke masa lalu—tahun 1995, saat pertama kali ia menapakkan kaki di sebuah pondok kecil di pesisir Muna Barat, Sulawesi Tenggara.
Waktu itu, Udin baru berusia 15 tahun. Ia datang dengan sebuah ransel lusuh berisi beberapa helai pakaian, buku tulis, mushaf Al-Qur’an, beberapa kitab terjemahan, dan semangat yang masih dibalut keraguan. Di antara semua itu, ada satu hal yang paling berat ia bawa: harapan besar dari orang tuanya—terutama sang ayah—yang dulu pernah mondok di PGA namun tak sempat menyelesaikannya. Kini, sang ayah meletakkan mimpi itu di pundak anak sulungnya.
Hari pertama di pondok ia lewati dengan perasaan campur aduk. Ada rasa bangga karena bisa mondok di tempat yang sejak SMP ia impikan. Ia merasa telah naik derajat—bukan hanya secara intelektual, tapi juga spiritual dan sosial. Ia pernah membaca tentang stratifikasi sosial masyarakat Jawa: priyayi, santri, dan abangan. Ia lahir dari keluarga abangan, namun menjadi santri adalah ikhtiar untuk naik kelas.
Namun, rasa bangga itu tak bisa sepenuhnya menutupi rasa sepi dan takut. Ia jauh dari rumah, dari ibunya yang sering menyelipkan uang seribu rupiah di dalam lipatan sarungnya, dan dari teman-teman sebayanya yang biasa bermain bola di lapangan setiap sore. Beruntung, La Ino—teman dekat sekaligus tetangganya—ikut mondok bersamanya. Mereka saling menguatkan, terutama di malam-malam pertama yang terasa sangat asing.
Hari-hari Awal: Dari Sungai ke Dapur Kayu
Hari-hari awalnya di pondok tidak mudah. Asrama yang ia tinggali masih berupa bangunan kayu dengan lantai tanah. Genset hanya menyala di jam-jam tertentu; selebihnya, mereka belajar dengan cahaya lampu minyak. Dingin malam sering menyusup melalui celah-celah papan.
Letak pondok yang berada di pinggir sungai membuat para santri terbiasa mandi dan mencuci pakaian di sana. Air sungai itu masih jernih, meskipun terkadang berubah keruh saat hujan atau ketika terjadi banjir di hulu. Dari lingkungan sederhana itu, Udin belajar arti hidup apa adanya—hidup yang penuh makna.
Ia sekamar dengan santri senior. Dari merekalah ia belajar mengatur waktu, membagi uang saku, memasak dengan tungku kayu, bahkan mencuci pakaian sendiri. Pondok menerapkan sistem masak mandiri—sendiri atau berkelompok. Udin dan La Ino biasanya ke pasar dua hari sekali untuk membeli bahan makanan. Meski lauk mereka sangat sederhana, suasana memasak yang penuh tawa menjadikannya kenangan yang tak terlupakan.
Guru, Adab, dan Mimpi Ibu
Ustadz dan ustadzah yang mengajar di pondok saat itu kebanyakan masih muda. Sebagian besar dari mereka adalah lulusan pesantren di Jawa atau mahasiswa dari Kendari yang diutus mengabdi di pedesaan. Mereka mengajar dengan ikhlas, walau dengan fasilitas seadanya.
Salah satu guru yang paling membekas dalam ingatan Udin adalah Ustadz Roni bin Abdul Aziz. Ia adalah sosok yang sederhana, namun penuh wibawa. Ustadz Roni tak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga menanamkan nilai-nilai adab. Dari beliaulah Udin belajar bahwa menjadi santri bukan hanya tentang kepintaran, tetapi tentang niat, ketulusan, dan akhlak.
Ada satu malam yang tak pernah ia lupakan: malam terakhir dari pekan ta’aruf. Saat itu, semua santri baru diminta menghadap Kyai satu per satu untuk mempraktikkan adab meminta izin. Pondok tempatnya belajar terkenal sangat ketat dalam hal adab. Bahkan cara bicara dan gerak tubuh pun diajarkan secara khusus, memadukan nilai-nilai Islam dengan tata krama ala pesantren Jawa. Malam itu, tubuhnya gemetar—bukan karena takut, tapi karena merasa sedang memasuki dunia yang agung dan penuh makna.
Keajaiban Kecil dari Sebuah Mimpi
Namun tak semua hal berjalan lancar. Ia pernah kehabisan bekal sebelum hari libur tiba. Biasanya, santri hanya bisa pulang ke rumah pada hari Jumat. Ia tidak tahu mengapa bekalnya cepat habis, mungkin karena sering berbagi makan dengan teman-teman. Hari itu, ia menahan lapar dan hanya bisa bersabar.
Lalu, pada hari kedua, ayahnya tiba-tiba datang membawakan makanan. Udin terkejut, karena ia tidak sempat memberi kabar. Belakangan, ia tahu dari ibunya bahwa malam sebelumnya sang ibu bermimpi tentang dirinya. Dalam mimpi itu, ia terlihat pulang ke rumah. Saat turun dari mobil angkutan pedesaan yang ia tumpangi terlihat kelelahan dan mabok kendaraan. Tanpa ragu, ibu menafsirkan mimpi itu sebagai tanda bahwa anaknya kehabisan bekal. Pagi harinya, ia meminta ayah segera datang ke pondok.
Sekarang Ia Kembali
Bertahun-tahun telah berlalu. Kini Udin telah menjadi guru. Ia juga mengajar di sebuah perguruan tinggi di kota hujan. Namun hatinya tetap tertambat pada dunia pesantren. Pondok memang telah berubah secara fisik, tapi spiritnya tetap sama.
Setiap kali ia mengajar, ia melihat bayangan dirinya sendiri di wajah santri-santri baru—yang masih bingung, rindu rumah, dan kadang menangis diam-diam di malam hari. Ia pun tidak hanya mengajar materi. Ia berusaha menjadi pelita kecil—seperti lampu minyak dahulu—yang meski redup, tetap memberi arah.
Pesan untuk Para Santri
Untuk setiap santri yang sedang berjuang:
Jangan pernah malu menjadi santri. Jangan takut menghadapi kesulitan. Pondok bukan sekolah biasa—ia adalah madrasah kehidupan. Tempat ini mungkin sederhana, tapi dari sinilah Allah menyiapkan jiwa-jiwa besar.
Mondoklah dengan niat yang lurus. Bersabarlah. Karena kelak, saat menoleh ke belakang, kamu akan bersyukur pernah berjalan di jalan ini.




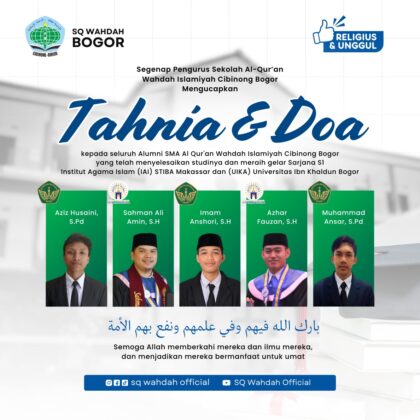
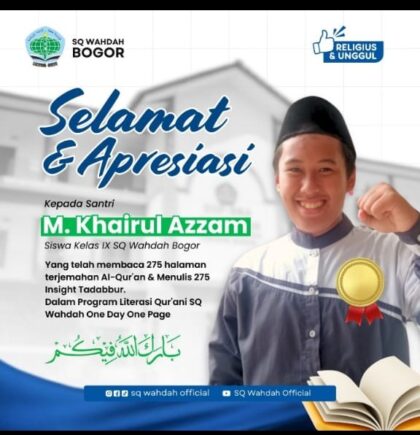


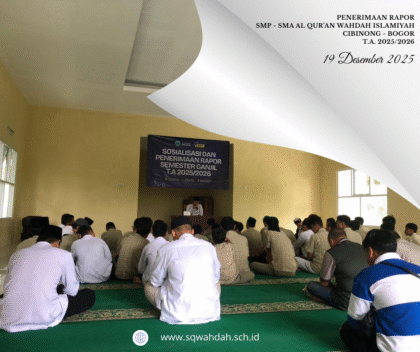







Komentar